Bivitri menekankan bahwa istilah alat negara itu tidak sekadar menjadi diksi semata, tapi mengandung makna khusus.
"Maknanya adalah dia memang diberikan kekuasaan untuk melindungi dan melaksanakan hal-hal yang langsung diperintahkan oleh kepala negara. Karena itu dia punya akses pada senjata dan dia punya legitimasi untuk melakukan kekerasan," jelasnya.
Kaitannya jika TNI aktif menduduki jabatan sipil, menurut Bivitri, kemungkinan kebijakan publik yang dihasilkan bukan berdasarkan partisipasi masyarakat, melainkan tunduk terhadap komando jabatan di atasnya.
"Dengan sistem komando, tentara itu dengan paradigmanya juga, dia akan misalnya membuat kebijakan pasti top-down. Tentara punya cara bertindak dan berpikir komandan, bilang apa saja mereka harus jawabnya siap. Kalau salah aja, siap salah. Gak mungkin dia bertanya, maaf-maaf komandan, 'saya mau nanya dulu nih, kita mau bertahan atau enggak?' Gak mungkin," terangnya.
Paradigma itu kata dia, jelas berbeda dengan sistem demokrasi yang butuh transparansi serta partisipasi publik.
Sementara militer tidak bisa terlalu transparan untuk hal-hal tertentu karena berkaitan dengan keamanan negara.
"Jadi kalau paradigma itu atau cara berpindah seperti itu masuk ke dalam pemerintahan yang harusnya demokratis, harusnya transparan dan lain sebagainya, gak akan kompatibel. Artinya nanti gak akan demokrasi lagi. Jadinya cenderung kepada otoritarianisme," pungkas Bivitri.
Sumber: Suara





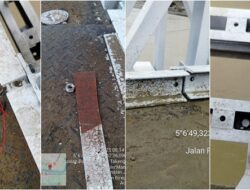





Artikel Terkait
KPK Selidiki Kasus Korupsi Kuota Haji 2024: Tersangka, Kronologi, dan Update Terbaru
Kedekatan Sarjan dengan Gibran di Kasus Suap Bupati Bekasi: KPK Diminta Usut Tuntas
Putri Candrawathi Dapat Remisi Natal 2025: Potongan Masa Hukuman 1 Bulan
Kasus Dana CSR BI: Perry Warjiyo Belum Disentuh KPK, Ini Analisis Hukum dan Daftar Tersangka Potensial